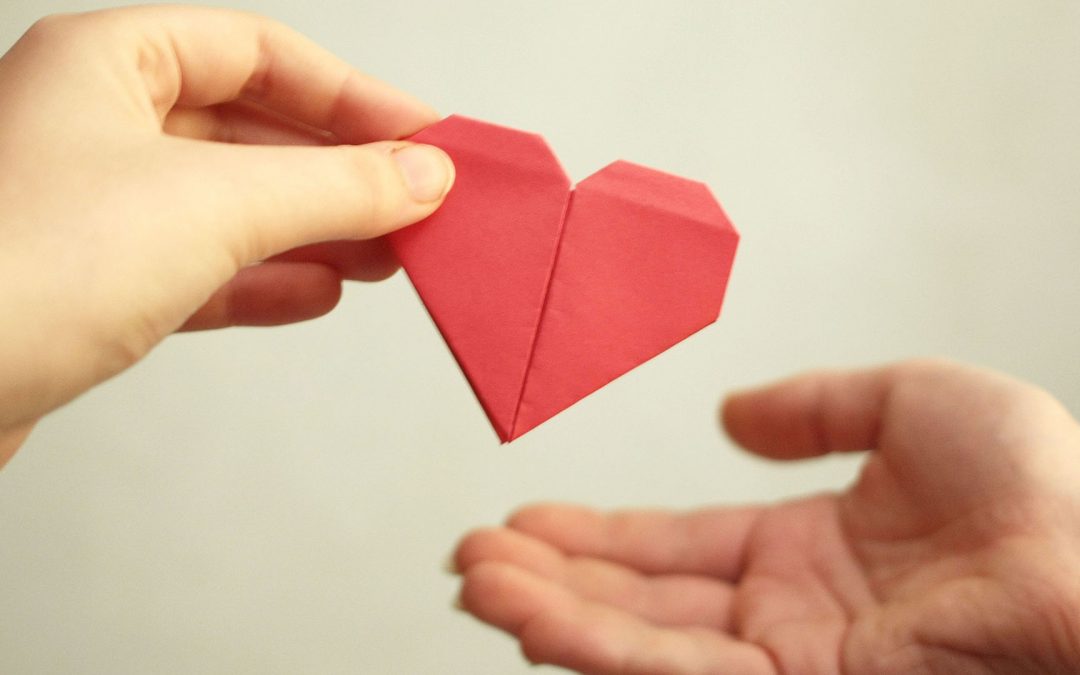Menafakuri Keikhlasan Bersedekah
Saat masih kecil, orangtua mendidik saya agar tak sungkan berbagi. Namun, saya pernah lupa pada didikan itu setelah sekian lama tidak tinggal bersama mereka.
Sebuah pembelaan tentu boleh dimunculkan. Yaitu ketika melihat daftar jumlah sumbangan orang-orang yang dimunculkan lewat running text di televisi. Nominal sumbangannya rata-rata mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dan kalau dipikir-pikir, saya merasa lebih tepat sebagai yang diberi ketimbang yang memberi.
Tetapi pada suatu waktu, sebuah kejadian memaksa saya mengubah anggapan tersebut. Beberapa tahun lalu, saya yang tinggal di Semarang hendak mengurus suatu keperluan di Bogor. Seorang teman mengundang mampir ke Tambun, Bekasi. Sukar menolak karena ia adalah teman masa kecil dan telah bertahun-tahun tidak bertemu. Maka berangkatlah saya ke Tambun terlebih dahulu.
Tidak ingin berlama-lama mengganggu, selepas magrib keesokan harinya saya bertolak dari Tambun menuju Bogor dengan menumpang bus. Sebelumnya, beberapa kali ke Bogor saya selalu naik kereta api via Stasiun Jatinegara dan Tebet. Dalam perjalanan, bus pun berhenti. Kalau tidak keliru di sekitar UKI. Kondektur bus kemudian memindahkan penumpang ke bus tujuan Bogor.
Hari makin malam dan mesin bus pengganti belum juga dinyalakan. Masih bertahan menambah penumpang dari total delapan orang yang sudah ada, termasuk saya. Satu jam berlalu pikiran mulai berkecamuk, sementara belum satupun penumpang baru. Bergantian kehadiran para pengamen sengaja saya abaikan sembari memejam mata di deretan bangku paling belakang.
Hampir dua jam tepat. Perasaan ini pun semakin jenuh, tapi tiba-tiba saya mendengar suara nyanyian seorang anak kecil dari arah depan. Ia dengan kualitas vokal apa adanya melantunkan lirik lagu ‘Yolanda’dari Kangen Band secara berulang-ulang. “Kamu di mana, dengan siapa/ Di sini aku menunggumu dan bertanya.”
Entah mengapa ketika mendengar nyanyiannya, menyeruak rasa iba. Rasa itu bercampur dengan simpati terhadap seniman jalanan kecil ini. Mungkin karena semua penumpang yang lain tidak memberinya receh, sayatergerak mengulurkan selembar uang saat ia datang mendekat. Saya juga meminta tolong kepadanya untuk mendendang lagu yang lain untuk dimainkan.
Cukup santun ia meminta maaf karena baru hafal satu kunci gitar. Wajahnya yang tampak lugu semakin membuat saya terenyuh. Dengan gitar sederhananya, saya lalu mengajaknya untuk belajar bersama. Satu lagu yang mungkin bisa bermanfaat baginya. Lagu yang bernafaskan nilai-nilai Islam, dan bukan lagu-lagu bertemakan cinta picisan.
Tak berapa lama, kami berdua pun asik bersenandung. Mendendangkan lagu ‘Surga-Mu’ dari Band Ungu. “Segala yang ada dalam hidupku/ Kusadari semua milik-Mu/ Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa/ Tunjukkan aku jalan lurus-Mu/ Untuk menggapai surga-Mu/ Terangiku dalam setiap langkah hidupku.”
Ketika usai bernyanyi bersama, pengamen kecil itu mengucap terima kasih sembari menyalami dan mencium tangan saya. Sejenak hati ini tertegun. Setelah bayang-bayangnya menghilang ditelan dinding pintu belakang bus, saya lalu memutar pandangan ke arah supir. Tidak berapa lama, mesin bus pun bergetar disertai derap langkah kaki sembilan orang penumpang baru yang naik melalui pintu depan. Entahlah, mungkin kebetulan, mungkin pula jawaban doa seluruh penumpang yang sudah lelah berjam-jam menanti. Yang pasti, kejadian itu mengesankan nala rini, dan selama berbulan-bulan terus membayangi pikiran saya.
Setelah kejadian tersebut, saya mulai sedikit mengerti kalau memberi tidak harus melihat nominalnya. Tetapi cukup dengan jujur pada kemampuan diri sendiri serta menyelami makna keikhlasan. Bersedekah jangan berpatok kepada orang karena bisa jadi ‘balasan’ member tak bisa dinalar.Terus terang, saya suka lupa bahkan tiba-tiba agak sukar menerima perkataan para ulama jika sedekah mendatangkan pahala untuk akhirat. Mengapa? Karena saya belum pernah kesana. Namun saya mulai percaya nasihat tentang membantu sesama yang akan diberi ‘ganjaran’ langsung di dunia. Tanpa bisa diduga bentuk, waktu, dan tempatnya.
Sejak kejadian itu, meskipun dengan kondisi keuangan pas-pasan, saya pasti memberikan sebagian rezeki yang dimiliki. Biasanya pada awal bulan setelah menghitung keperluan pokok hingga akhir bulan. Padahal, jujur saja jika ‘uang sisa’ bulanan itu nominalnya tidak seberapa, bahkan beberapa kali ‘minus’. Walaupun menyadari hal ini, saya tetap menguatkan tekad dan setengah nekat untuk bisa berbagi kepada yang lain. Dan alhamdulilah, pastinya bukan suatu kebetulan jika keperluan hidup bulanan saya tidak pernah sampai kekurangan. Bahkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak, selalu ada saja ‘uluran tangan’ yang datang membantu membuka pintu rezeki untuk saya ikhtiarkan.
Kenyataan ini membuat saya semakin percaya kalau bersedekah, yakni dengan jujur pada kemampuan dan niat ikhlas lillahi ta’ala, sama sekali tak akan pernah membikin kita menjadi kekurangan, apalagi kelaparan. Yang didapati—sebagaimana yang saya alami—adalah hal sebaliknya. Dan ini belum menyoal pahala yang bakal didapatkan di akhirat kelak.Apa yang dirasakan itu membuat saya tidak ragu-ragu member lebih banyak ketika saya diberi rezeki lebih dari yang dibutuhkan. Itu karena saya yakin rezeki yang disedekahkan tidak akan pernah hilang.
Saya pun terus-menerus membiasakan diri, bahkan terkadang sampai lupa menghitung keperluan bulanan. Saya baru mengingatnya setelah bersedekah, tapi alhamdulillah kebiasaan lupa itu tidak pernah saya sesali. Jika menganggap diri sendiri bodoh karena berbuat demikian, kiranya saya sama saja dengan orang yang hartanya berlimpah, namun secara sadar enggan bersedekah. Keraguan bersedekah justru bisa membuat saya terjerumus pada lingkaran kegelisahan. Yaitu orang yang hidupnya jauh berkecukupan, tapi sekaligus takut kekurangan. Semoga kita semua senantiasa mendapat hidayah dari Allah agar tidak ragu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. (Zamroni)