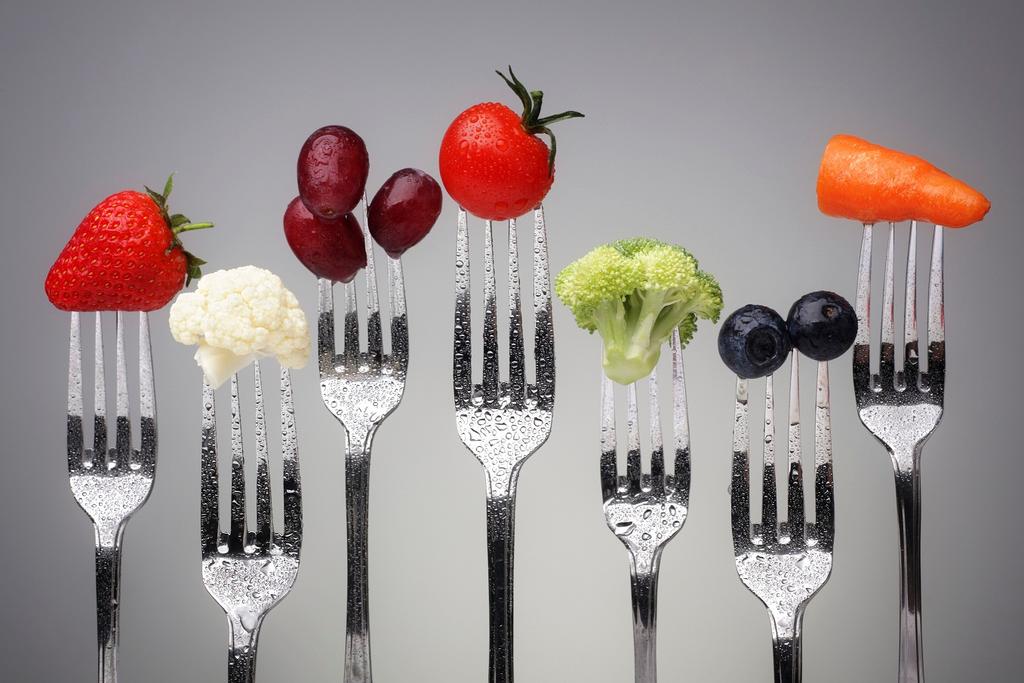Mengendalikan Nafsu Makan
“Tidak ada satu tempat pun yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi dia beberapa suap makanan saja, asal dapat menegakkan tulang rusuknya.” (HR Ahmad dan Tirmidzi)
Islam sangat mengecam tindakan berlebihan dalam hal apa pun. Salah satunya mengonsumsi makanan. Mengapa? Sebab, tindakan berlebihan sangat dekat dengan kemudharatan, jauh dari kebaikan, dan hampa keberkahan. Maka, dalam konteks “makan memakan”, ada pernyataan menarik dari Rasulullah saw, yakni “sumber segala penyakit adalah memasukkan makanan di atas makanan”. Apa maknanya? Kita memasukan makanan ke perut yang sudah penuh dengan makanan.
Karena perut bisa menjadi “rumah penyakit”. Berpantang dan tidak berlebihan adalah pangkal segala obat. Adapun kata kuncinya adalah ”pengendalian diri”. Di sinilah Islam memberikan tuntunan menyeluruh dalam proses pengendalian diri nafsu makan.
Pertama, mengendalikan nafsu makan dengan keimanan.
Etika atau adab-adab makan sangat ditentukan oleh visi atau cara pandang yang mendasarinya. Itulah mengapa, terdapat perbedaan mendasar dalam memandang aktivitas makan antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Orang beriman makan untuk tujuan mendapatkan energi atau tenaga agar bisa beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta’ala.
Adapun orang kafir, mereka makan sekadar mendapatkan kesenangan, memuaskan nafsu, atau mendapatkan energi untuk berbuat kerusakan. Maka, Rasulullah saw memberikan label kepada orang-orang beriman sebagai sekelompok orang yang hanya makan ketika lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya, mereka tidak mengisi penuh perutnya dengan makanan, walaupun makanan yang dikonsumsi didapat dari sumber halal dan halal pula zatnya.
Hal ini membawa berkah tersendiri. Orang beriman menjadi orang-orang yang ”tidak ribet” dalam urusan makan. Dia akan makan sesuai kebutuhan, tidak mempersulit diri, tidak mencela makanan, dan mensyukuri makanan apa pun yang direzekikan kepada mereka. Lain halnya dengan orang kafir. Untuk mendapatkan kepuasan, mereka harus makan lebih banyak, mempersulit diri, tidak mensyukuri makanan yang ada, berkeluh kesah dan mencemooh apabila makanan yang dihidangkan kepadanya tidak sesuai selera.
Maka, Rasulullah menyifati mereka makan dengan tujuh perut, sedangkan orang beriman makan dengan satu perut. “Orang kafir itu makan dalam tujuh perut sedangkan orang mukmin makan dalam satu perut.” (HR. Muslim)
Analogi ”tujuh perut” sebagaimana diungkapkan Rasulullah ini sangat menarik. Apa maknanya? Konsep tujuh ini tidak hanya dikenal dalam terminologi perut saja, yang berarti banyak. Dalam ilmu tasawuf dikenal pula konsep tujuh, yaitu tujuh maqam, tujuh tingkatan atau tujuh terminal untuk”bersatu” dengan Allah al-Khaliq. Al-Quran pun menyebut kata ”tujuh” ini berkali-kali, khususnya dalam konteks penciptaan. Salah satunya dalam surah al-Mulk [67]: 3, “(Allah-lah) yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?”
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, konsep ”tujuh” kini mulai terkuak kebenarannya. Kita dapat memahaminya melalui pendekatan fisika partikel. Konsep langit bisa diterjemahkan dan digambarkan sebagai ”dimensi” atau ”lapisan”. Setiap dimensi memiliki karakteristik dan ciri-cirinya tersendiri. Ketika seseorang makan dan minum dalam dimensi fisik, makanannya pun adalah makan yang bersifat fisik. Ketika dia makan dalam dimensi yang berbeda, asupan nutrisinya pun berbeda.
Jadi orang yang makan dengan tujuh perut, selain berlebih-lebihan, dapat diartikan pula sebagai orang-orang yang memberi makan jiwanya (sebagai dimensi yang berada di luar fisik) dengan makanan duniawi, yaitu berupa kerakusan makan yang diperturutkan. Padahal, seorang muslim seyogyanya mampu membedakan antara makanan fisik dengan makanan ruhani. Zat-zat nutrisi yang paling tepat dan paling menyehatkan hati—sebagai bagian dari dimensi non fisik—adalah berzikir atau senantiasa mengingat Allah SWT, menjalankan aneka ketaatan, menyayangi sesama, menyantuni anak yatim, mendoakan orang lain agar selamat dunia akhirat, dan sebagainya. Dengan makan secara berlebihan, seseorang telah memaksa dimensi lain dari dirinya untuk menjadi sosok yang rakus dan tidak pernah puas.
Kedua, mengendalikan nafsu makan dengan saum.
Islam mensyariatkan ibadah saum pada waktu-waktu tertentu, semisal pada Bulan Ramadan, setiap muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Kita kemudian diperintahkan untuk menyempurnakannya dengan saum 6 hari pada Bulan Syawwal. Saum 6 hari ini termasuk saum yang bersifat sunnah atau anjuran. Tidak berhenti sampai di sini, kita pun sangat dianjurkan membiasakan saum-saum sunnah lainnya, semisal saum Senin Kamis, saum Arafah, saum Dawud, saum tiga hari pada pertengahan bulan, dan lainnya.
Ada banyak keutamaan dari ibadah saum ini. Satu yang terpenting adalah mengendalikan asupan makanan yang berlebih. Dengan saum sepanjang hari, diawali pada Subuh hari sampai datangnya waktu Maghrib, kita dituntut menurunkan jumlah total dari asupan makanan. Hal ini pada akhirnya mengkondisikan seseorang untuk senantiasa mampu mengendalikan nafsu makannya.
Ketiga, mengendalikan nafsu makan dengan membatasi asupan makanan.
Dalam hal ini, Rasulullah saw memberikan panduan yang sangat jelas. Beliau mengajarkan aturan pertigaan sebagai panduan terkait asupan makanan, yaitu sepertiga untuk makanan padat, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara (Musnad Ahmad). Hal ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh berlebihan dalam makan. Dia boleh makan dengan catatan harus proporsional, tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan.
Contoh lainnya, Rasulullah pun mengajarkan kita agar makan dengan tiga jari. Dalam sebuah hadis riwayat Ka’ab bin Malik disebutkan bahwa, “Sungguh Rasulullah saw makan dengan menggunakan tiga jari.” (HR Muslim dan Abu Dawud). Hadis ini kembali menunjukkan pentingnya kita memperhatikan jumlah asupan makanan agar berada dalam kondisi proporsional.
***
Dalam upaya mengendalikan nafsu makan dengan membatasi asupan makanan, kita dapat merujuk pada pendapatnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam salah satu karya masterpiece-nya, yaitu Thibbun Nabawi. Beliau membagi tingkat kebutuhan manusia akan makanan ke dalam tiga kondisi. Pertama, adh-dharurat, yaitu asupan nutrisi minimum yang sangat diperlukan manusia untuk bisa mempertahankan kondisi tubuhnya agar tetap baik. Kedua, al-hajât, yaitu asupan nutrisi yang melebihi aspek darurat; bersifat pemuasan akan kebutuhan untuk mengobati rasa lapar. Ketiga, al-fadhl, yaitu kelebihan dari asupan nutrisi yang dibutuhkan, dengan kata lain kelebihan asupan di luar kebutuhan.
Seorang muslim dianjurkan makan dalam dua kondisi pertama, yaitu yang bersifat dharurat atau hajat. Adapun yang bersifat kelebihan di luar kebutuhan sebaiknya dihindari karena apabila diperturutkan dan menjadi kebiasaan, ia dapat membawa konsekuensi negatif bagi kesehatan. (Tauhid Nur Azhar)
sumber foto: suarawajarfm.com